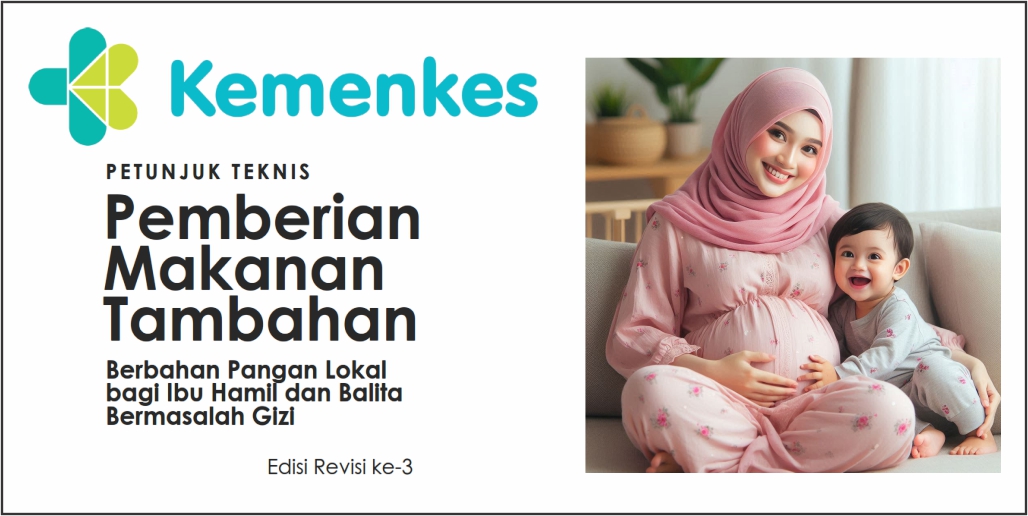Kementerian Kesehatan Republik Indonesia baru-baru ini menerbitkan Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil dan Balita Bermasalah Gizi, edisi revisi ketiga tahun 2025. Petunjuk teknis ini hadir sebagai respons terhadap masih tingginya masalah gizi di Indonesia, khususnya pada kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita. Revisi ini juga menjawab kebutuhan di lapangan yang semakin kompleks, serta memperkuat strategi berbasis potensi lokal untuk mendukung perbaikan status gizi masyarakat.
Seperti yang dijelaskan dalam dokumen tersebut, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Gizi yang baik menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Namun realita di lapangan menunjukkan bahwa ibu hamil dan balita masih menjadi kelompok yang sangat rentan mengalami kekurangan gizi. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi wasting pada balita mencapai 8,5%, sementara stunting berada di angka 21,5%. Di sisi lain, prevalensi risiko Kurang Energi Kronis (KEK) pada wanita usia subur tercatat sebesar 20,6%, dan pada ibu hamil sebesar 16,9%. Tak hanya itu, anemia pada ibu hamil juga masih menjadi masalah besar dengan prevalensi mencapai 27,7%.
Permasalahan gizi ini tidak berdiri sendiri. Ada banyak faktor penyebab, baik langsung maupun tidak langsung. Di antaranya adalah rendahnya asupan makanan bergizi, seringnya terinfeksi penyakit, pola asuh yang belum optimal, hingga faktor sosial ekonomi dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Berdasarkan Survei Diet Total (SDT) tahun 2014, hampir 49% balita di Indonesia memiliki asupan energi kurang dari 100% kebutuhan hariannya, dan 6,8% bahkan sangat kurang. Sementara itu, sekitar 23,6% balita memiliki asupan protein yang kurang, dan keberagaman makanan juga masih menjadi tantangan. Pada kelompok ibu hamil, hasil SDT 2024 menunjukkan lebih dari separuh mengalami asupan energi dan protein yang sangat rendah.
Menjawab tantangan ini, Kementerian Kesehatan mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual, dengan memanfaatkan kekayaan pangan lokal yang dimiliki hampir seluruh wilayah Indonesia. PMT berbahan pangan lokal bukan sekadar program intervensi, tetapi juga bentuk konkret penguatan ketahanan pangan rumah tangga serta pengurangan ketergantungan pada produk-produk luar. Dalam pelaksanaannya, PMT lokal tidak hanya bertujuan menambah asupan energi dan protein, tetapi juga menjadi sarana edukasi gizi, pemberdayaan masyarakat, serta langkah kecil untuk mendukung kelestarian lingkungan.
Dokumen petunjuk teknis ini memuat alur tata laksana yang lebih terstruktur, dimulai dari deteksi dini kondisi gizi ibu hamil dan balita, hingga tata laksana pemberian PMT lokal yang disesuaikan dengan jenis masalah gizinya. Untuk ibu hamil, PMT diberikan pada mereka yang teridentifikasi mengalami KEK atau berisiko KEK, dengan kriteria Indeks Massa Tubuh (IMT) pra hamil atau trimester pertama di bawah 18,5 kg/m², atau Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm. PMT diberikan selama minimal 120 hari, disertai dengan edukasi gizi dan pemantauan rutin berat badan ibu sesuai usia kehamilan.
Balita yang menjadi sasaran PMT lokal adalah mereka yang mengalami berat badan tidak naik, berat badan kurang, atau gizi kurang, baik dengan maupun tanpa stunting. Program ini tidak mencakup balita gizi buruk, karena penanganannya membutuhkan intervensi medis lebih lanjut di fasilitas rujukan. Alur tata laksana balita bermasalah gizi cukup rinci, dimulai dari deteksi dini di posyandu oleh kader, konfirmasi status gizi di puskesmas, pemeriksaan red flag oleh dokter, hingga pemberian PMT selama 14 hingga 56 hari tergantung jenis masalahnya.
Yang menarik, petunjuk teknis ini tidak hanya membahas aspek teknis intervensi gizi, tetapi juga memberikan penekanan pada prinsip keberlanjutan dan pelibatan masyarakat. PMT berbahan pangan lokal didesain sebagai makanan siap santap, yang bisa berupa makanan lengkap atau kudapan padat gizi. Komposisinya terdiri dari makanan pokok, lauk hewani dan nabati, sayuran, buah, dan lemak sehat. Misalnya, satu porsi PMT untuk ibu hamil bisa berisi nasi, telur, tempe, sayur bayam, dan buah pepaya. Untuk balita, porsinya disesuaikan dengan usia dan kebutuhan energi hariannya. Semuanya dibuat dengan memperhatikan prinsip gizi seimbang dan preferensi lokal, serta diutamakan menggunakan bahan pangan yang telah difortifikasi seperti garam beryodium atau minyak goreng fortifikasi.
Selain penyediaan makanan, petunjuk teknis ini menekankan pentingnya edukasi yang menyertai proses pemberian PMT. Edukasi diberikan dalam bentuk konseling, penyuluhan, hingga demonstrasi pengolahan makanan. Harapannya, pengetahuan ini bisa diterapkan keluarga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dampaknya lebih berkelanjutan.
Dalam hal penyelenggaraan, petunjuk teknis membagi peran antar lintas sektor dengan sangat jelas. Pemerintah pusat bertanggung jawab menyusun kebijakan dan melakukan sosialisasi serta evaluasi. Pemerintah daerah dan puskesmas mengoordinasikan pelaksanaan di lapangan, mulai dari verifikasi sasaran, penyusunan siklus menu, hingga pelatihan kader. Di tingkat desa dan posyandu, peran kader sangat krusial dalam pemantauan pertumbuhan, pemberian PMT, hingga pelaporan. Bahkan, keluarga juga dilibatkan sebagai agen utama perubahan, terutama dalam hal pola makan dan perilaku gizi.
Pemantauan dan evaluasi menjadi bagian penting dalam program ini. Pemantauan berat badan dan status gizi dilakukan mingguan atau bulanan tergantung pada jenis kasus. Kriteria keberhasilan ditetapkan secara spesifik, misalnya berat badan balita naik sesuai standar pertumbuhan, atau ibu hamil mengalami kenaikan BB yang sesuai dengan usia kehamilan. Jika tidak terjadi perbaikan dalam dua minggu, maka balita harus dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.
Secara keseluruhan, Petunjuk Teknis PMT Lokal 2025 ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga mencerminkan semangat baru dalam penanggulangan masalah gizi yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar soal makanan tambahan, tapi gerakan kolaboratif dari semua lini—dari keluarga, kader, puskesmas, hingga pembuat kebijakan—untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan bebas dari stunting.